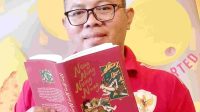Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Jakarta, 17 Agustus 2025 – Pemerintah merayakan 80 tahun kemerdekaan dengan klaim besar tentang “delapan kemerdekaan”: merdeka dari malnutrisi, impor beras, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbatasan layanan kesehatan, ketergantungan politik luar negeri, dan korupsi. Namun di balik jargon itu, kenyataan dihadapi rakyat justru penuh kontradiksi: kerja panjang tanpa henti, upah rendah, diskriminasi, hingga ketidakpastian ekonomi yang kian menghimpit. Alih-alih merdeka, mayoritas rakyat justru masih terbelenggu oleh sistem kerja eksploitatif.
Menanggapi situasi itu, Panggung Merdeka 100% menggelar diskusi paralel kedua bertajuk “Bekerja Lebih Sedikit, Hidup Lebih Baik, Dunia yang Adil untuk Semua”. Diskusi ini menghadirkan Ajeng Anggraini (Perempuan Mahardhika), Francesco Hugo (Suara Muda Kelas Pekerja), Echa Waode (Arus Pelangi), dan Guruh Riyanto (SINDIKASI), difasilitasi Tyas Widuri dan Andini N (Perempuan Mahardhika).
Ajeng Anggraini menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini memaksa rakyat bekerja tanpa henti demi mengejar target pertumbuhan yang eksploitatif. Menurutnya, kerja seharusnya menjadi sarana untuk hidup lebih layak, bukan justru membuat rakyat terjebak dalam siklus hidup untuk kerja tanpa henti.
“Negara hanya fokus pada percepatan ekonomi dengan upah rendah. Hidup kita direduksi jadi mesin kerja: tanpa istirahat, tanpa cuti, tanpa ruang bersosialisasi. Perempuan bahkan menanggung beban ganda, publik dan domestik, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus kasus kekerasannya atau sekadar merawat budaya. Kita harus membalik logika itu: kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja,” ujar Ajeng.
Sementara itu, Francesco Hugo menggambarkan realitas anak muda yang hidup dalam jeratan kerja yang penuh ketidakpastian. Ia menyoroti bagaimana generasi muda dipaksa menerima kondisi kerja yang tidak tetap, tanpa jaminan, dan rawan dieksploitasi.
“Kondisi kerja kita penuh eksploitasi halus: gaji stagnan, inflasi naik, dan ancaman layoff tiba-tiba. Anak muda jadi depolitisasi, dianggap keren kalau bisa hidup frugal padahal hanya bertahan hidup. Masa depan yang adil itu butuh kerja yang transparan, demokratis, dan kolektif. Koperasi bisa jadi jalan—bukan untuk jadi kapitalis kecil-kecilan, tapi membangun solidaritas untuk melawan hegemoni kapitalis,” tegas Hugo.
Selanjutnya, Echa Waode turut menyoroti diskriminasi di tempat kerja yang dialami pekerja LGBTIQ+ di Indonesia, di mana orientasi seksual dan identitas gender kerap dijadikan alasan untuk menutup akses terhadap pekerjaan layak.
“Di negeri ini, orientasi seksual dan identitas gender sering dijadikan alasan menutup akses kerja. Padahal yang menentukan itu skill, bukan penampilan atau siapa yang kita cintai. Negara bukan hanya gagal menyediakan kerja layak, tapi juga memungut pajak dari kami sembari mendiskriminasi. Kita harus melawan stigma—karena yang bobrok bukan identitas kita, melainkan negara yang menindas,” kata Echa.
Di sisi lain, Guruh Riyanto menekankan bahwa indikator ekonomi dominan seperti GDP (Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto) tidak pernah cukup untuk menggambarkan realitas kehidupan rakyat. Ukuran tersebut pada dasarnya hanya memperkuat kapitalisme, sementara kesejahteraan nyata pekerja justru diabaikan.
“Pertumbuhan ekonomi kita sering dipuja, padahal ditopang konsumsi yang putus asa. Kita perlu menggeser ukuran dari GDP ke kesejahteraan nyata pekerja. Dengan kemajuan teknologi dan AI, seharusnya waktu kerja bisa dikurangi, bukan malah ditambah. Pajak robot, pajak AI, bisa jadi jalan untuk memperkuat jaminan sosial. Intinya: kerja tidak boleh lagi menjadi penjara, melainkan pintu menuju kehidupan yang layak,” jelas Guruh.
Diskusi ini menegaskan pentingnya membangun imajinasi politik-ekonomi yang membebaskan, yakni keluar dari jeratan ukuran-ukuran kapitalistik semata dan berani merumuskan arah pembangunan yang berkeadilan. Ruang percakapan seperti ini tidak hanya menjadi wadah berbagi pengalaman dan kritik terhadap kondisi kerja, tetapi juga menjadi fondasi untuk membayangkan kemungkinan baru—sebuah masyarakat di mana kerja tidak lagi menjadi sumber penindasan. Dari sini, imajinasi kolektif yang lebih progresif dapat tumbuh, menantang status quo, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil bagi semua.
“Kita terbiasa menerima eksploitasi seolah wajar, sehingga jarang membayangkan dunia lain yang adil. Padahal, keberanian berimajinasi itulah yang membuka jalan perubahan. Kolektif lintas gerakan, koperasi, hingga strategi pengorganisiran adalah kunci menuju dunia kerja yang adil,” pungkas Tyas dan Andini sebagai fasilitator.
Jurnalis: Hendra